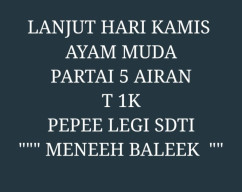Syafruddin Prawiranegara Penantang Kekuasaan dari Jakarta hingga Hutan Sumatra

Pada paruh kedua tahun 1950-an, Indonesia berada di tengah pusaran krisis: ekonomi melemah, politik berkecamuk, dan hubungan pusat daerah memanas. Di tengah arus besar sejarah ini, nama Syafruddin Prawiranegara tokoh ekonomi, pemikir negara, sekaligus politisi Masyumi muncul sebagai salah satu figur paling menentukan dan paling kontroversial.
Awal Krisis: Indonesia Tahun 1957 yang Bergejolak
Ekonomi Indonesia pada 1957 sedang terseret ke jurang pelemahan. Situasi politik pun semakin panas. Di tengah kondisi penuh ketidakpastian ini, muncul sentimen luas yang menyalahkan perusahaan-perusahaan asing, terutama milik Belanda, sebagai biang kerok keterpurukan ekonomi.
Pandangan publik mulai berbalik menentang tokoh-tokoh yang dianggap pro-investasi asing—dan Syafruddin termasuk di antaranya. Ia menjadi sasaran kritik keras.
Pada saat yang sama, Sukarno merancang Demokrasi Terpimpin, sebuah konsep politik yang ditentang oleh akar rumput Masyumi. Hubungan antara Masyumi dan PNI pun retak, dan pada 8 Januari 1957, Masyumi resmi keluar dari koalisi pemerintah—tanda bahwa badai besar sedang menuju Jakarta.
Nasionalisasi Perusahaan Belanda & Ketegangan Baru
Setelah Belanda menggagalkan pembahasan Papua Barat di Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB (29 November 1957), Sukarno memerintahkan pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat buruh dan tentara.
Syafruddin Prawiranegara berdiri di garis berlawanan. Ia menentang nasionalisasi, mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, bahkan mengkritiknya secara terbuka di hadapan Sukarno.
Keberaniannya berbuah risiko. Ketika terjadi percobaan pembunuhan Sukarno di Cikini (30 November 1957), sejumlah pelaku berasal dari sayap pemuda Masyumi, dan Syafruddin ikut terseret dalam penyelidikan.
Media menyerang, ancaman telepon datang, kelompok paramiliter mengintimidasi. Pada Januari 1958, Syafruddin memilih meninggalkan Jakarta menuju Padang demi keselamatannya. Ia mengakui, “Aku pergi karena tidak bersedia mati konyol.”
Rapat-Rapat Rahasia Menuju Pemberontakan
Di Sumatra, Syafruddin Prawiranegara bertemu tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Maludin Simbolon. Ada wacana menjadikan Sumatra sebagai negara merdeka.
Namun Syafruddin Prawiranegara menolak gagasan memisahkan diri. Ia memilih perjuangan politik: menuntut pembubaran Kabinet Djuanda dan membentuk pemerintahan baru di bawah Hatta dan Sri Sultan HB IX.
Di balik layar, CIA sudah terlibat diam-diam: kiriman senjata dan dana mulai mengalir untuk mengguncang pemerintahan Sukarno. Tetapi dukungan Amerika saat itu masih samar belum mau tampil terang-terangan.
Jatuhnya Jabatan dan Deklarasi PRRI
Karena aktivitas politiknya, jabatan Syafruddin Prawiranegara sebagai Gubernur Bank Indonesia dicabut pada 1 Februari 1958.
Pada 15 Februari 1958, Kolonel Ahmad Husein mendeklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang. Syafruddin Prawiranegara dijadikan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Syafruddin menyatakan kelak bahwa ia tidak pernah menjadi penggagas PRRI, namun merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan prinsip kenegaraan yang ia anggap benar.
Serangan Pemerintah Pusat dan Perjuangan Gerilya
Pemerintah pusat segera memerintahkan penangkapan seluruh pimpinan PRRI. Pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menyerang Padang dan Bukittinggi.
Pada April 1958, Padang jatuh tanpa perlawanan berarti; 5 Mei, Bukittinggi menyusul.
Kegagalan demi kegagalan membuat PRRI mundur menjadi gerilya hutan. Amerika Serikat menarik dukungan. Namun Syafruddin tetap keras kepala, bahkan pada ulang tahun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menyerukan perlunya Indonesia kembali menjadi negara serikat.
Puncaknya, pada 8 Februari 1960, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memproklamasikan Republik Persatuan Indonesia (RPI) di Bonjol, dengan Syafruddin sebagai presiden. Meski idealisme tinggi, kondisi lapangan tak mendukung: satu per satu basis PRRI direbut, termasuk Koto Tinggi (1960).
Syafruddin Prawiranegara dan para pemimpin lain akhirnya hidup dalam pelarian di hutan, terputus dari komunikasi dan logistik
Amnesti, Keruntuhan PRRI, dan Penyerahan Diri
Pada akhir 1960, Jenderal AH Nasution mengumumkan amnesti bagi tentara PRRI. Banyak pasukan menyerah antara 1960–1961, memecah kekuatan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Syafruddin Prawiranegara masih bertahan, tetapi semakin tersudut. Setelah memberi perintah gencatan senjata pada 17 Agustus 1961, ia menyerahkan diri pada 25 Agustus 1961 bersama Assaat dan Burhanuddin Harahap di sekitar Padang Sidempuan.
Awalnya ia bebas karena amnesti Sukarno, namun pada Maret 1962 ia kembali ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan, hingga akhirnya dibebaskan pada 26 Juli 1966, menjelang lengsernya Sukarno.
Sebuah Kisah Tentang Prinsip, Kekuasaan, dan Harga Sebuah Perjuangan
Kisah Syafruddin Prawiranegara adalah kisah idealisme yang bertabrakan dengan realitas politik. Ia menolak menjadi boneka kekuasaan, tetapi juga terseret dalam permainan besar yang melibatkan tentara, partai politik, hingga Central Intelligence Agency (CIA).
Ia bukan sekadar tokoh yang dikejar-kejar sejarah, melainkan seseorang yang berupaya mempertahankan keyakinannya hingga titik penghabisan meski harus bergerilya di hutan, kehilangan jabatan, dan merasakan dinginnya penjara. (*)
Editor : Bambang Harianto